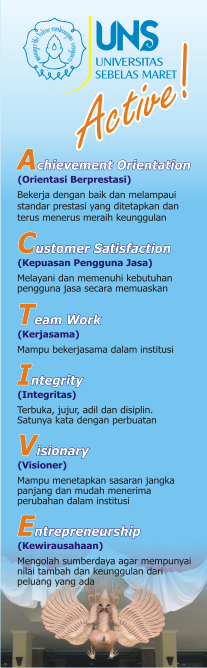Ketika Terorisme Menjadi Musuh Bersama
Eskalasi aksi terorisme meningkat tajam pascaperistiwa “9/11” di Amerika. Setidaknya polisi menangkap 800 orang tersangka kasus peledakan bom di sejumlah kota di tanah air dan setidaknya 30 persen propinsi di Indonesia dinyatakan rawan aksi terorisme. Propinsi-propinsi itu, meliputi: Aceh, Sumatra Utara, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, dan sejumlah wilayah di Indonesia timur.
Demikian ungkap Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjend. Esa Permadi pada Seminar Nasional Kebangkitan Nasional Menuju Indonesia Damai Tanpa Kekerasan dan Radikalisme, Jumat (25/5), di Ruang Sidang II Kantor Pusat UNS Solo. Esa menambahkan, setidaknya ada tujuh kelompok pelaku terorisme yang “bermain” di Indonesia. Ia merinci kelompok-kelompok itu, antara lain: DI/NII, Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansharut Tauhid, Tauhid Waljihad, Laskar Jundullah, Batalyon Abu Bakar, dan Taliban Melayu.
“Fenomena aksi terorisme di Indonesia merupakan fenomena gunung es. Yang terjadi selama ini hanyalah puncaknya. Sedangkan di bagian bawah banyak pelaku atau calon pelaku yang berusaha untuk muncul ke permukaan,” ungkap Esa. Ia menilai kasus terorisme di Indonesia tidak disebabkan oleh masalah tunggal tetapi merupakan akumulasi dari masalah politik ekonomi sosial budaya (poleksosbud).
Ketiga faktor itu, lanjut Esa, mengkristal menjadi ketidakadilan yang meluas. Hingga pada akhirnya dieksploitir dengan ideologi yang mengatasnamakan agama dengan paham dan penafsiran ekstrem terhadap agama.
Hal senada juga diungkapkan Guru Besar FISIP UNS Prof. Pawito. Pawito mengungkapkan bahwa ketidakadilan dapat menjadi faktor penyebab berkembangnya terorisme. “Karena praktik ketidakadilan pada dasarnya adalah tindakan melukai nurani yang menimbulkan sakit hati dan rasa dendam yang kemudian menyebabkan kecenderungan kejiwaan merasa teralienasi dan memprovokasi tindakan balasan,” ungkap Dekan FISIP UNS itu.
Dosen Universitas Gadjah Mada Prof. Tadjuddin Noer Effendi mengungkapkan hal yang sama. Ia berpendapat, bonus demografi yang dialami bangsa Indonesia belum termanfaatkan secara optimal. Ia menjelaskan, “Bonus demografi merupakan situasi saat struktur penduduk bercirikan usia produktif lebih besar daripada usia non-produktif sehingga beban tanggungan (dependency ratio) relatif rendah. Struktur umur penduduk seperti itu dapat menjadi berkah dan dapat juga menjadi beban dan sumber masalah sosial bila tidak dimanfaatkan secara optimal,” ungkapnya.
Namun, lanjut Tadjuddin, kelebihan angkatan kerja dan sedikitnya peluang kerja ditambah kompetisi dan persaingan di pasar kerja yang semakin ketat menyebabkan pengangguran terbuka usia remaja mengalami tekanan dan membuat mereka frustrasi. Hal ini memicu terjadinya kecemburuan sosial sebagai akibat dari gaya hidup hedonis kelas menengah usia muda yang cenderung ditiru para pengangguran terbuka remaja yang secara ekonomi tidak mampu.
“Kecemburuan sosial itu dapat saja menjadi sumber konflik laten. Ketika ada masalah sepele, seperti bersenggolan dan salah pengertian ketika berinteraksi sosial dalam kehidupan bisa sebagai penyulut emosi diikuti dengan konflik terbuka kemudian memicu para remaja untuk melakukan tindakan kekerasan,” papar Tadjuddin.
Tadjuddin berpendapat, untuk mencegah tindakan kekerasan yang dilakukan kalangan remaja dapat dilakukan dengan memanfaatkan bonus demografi secara optimal. Perlu memperluas kewiraswastaan, kursus ekonomi kreatif, pelatihan ketrampilan, penyelenggaraan bursa pasar kerja, dan kebijakan yang mendorong remaja agar dapat berusaha dan bekerja.
Sebelum mengakhiri presentasinya, Tadjuddin berpesan, “Jangan biarkan mereka mencari jalan sendiri untuk menghadapi dan memecahkan masalah yang sedang mereka hadapi.”